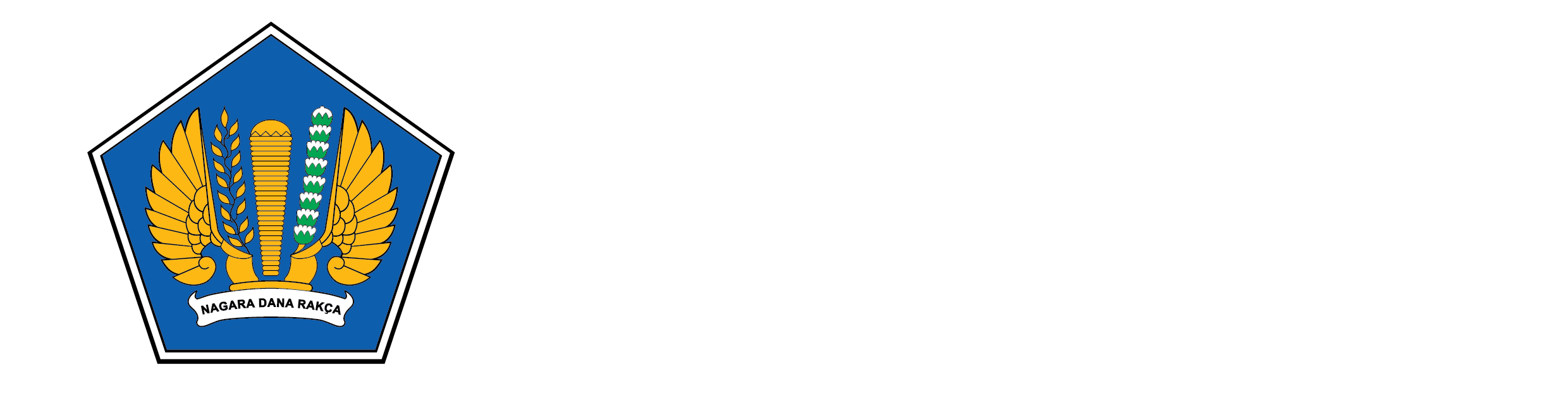Pernah nggak sih kamu merasa gajimu dari tahun ke tahun cenderung stagnan, tapi pengeluaran justru makin nggak karuan? Harga bahan pokok naik, biaya sekolah anak makin mahal, cicilan terus jalan, belum lagi kebutuhan mendadak yang sering datang tanpa aba-aba. Sementara penghasilan jalan di tempat, biaya hidup malah terus merangkak. Seperti berlari di treadmill rasanya capek dan berkeringat, akan tetapi tetap di titik yang sama. Ternyata, ini bukan cuma ceritamu atau keluargamu. Banyak rumah tangga Indonesia mengalami hal serupa. Dan menariknya, ini bukan hanya soal kondisi rumah tangga, tapi juga gambaran lebih besar tentang perekonomian Indonesia yang sedang menghadapi apa yang disebut para ekonom sebagai middle income trap.
Jebakan Untuk Maju
Secara teknis, middle income trap adalah kondisi saat sebuah negara berhasil keluar dari status berpendapatan rendah, namun tertahan di kelompok pendapatan menengah karena laju pertumbuhan ekonominya melambat. Umumnya kondisi ini disebabkan oleh biaya produksi sudah tidak lagi murah untuk menarik investor yang mencari tenaga kerja murah, tetapi kualitas inovasi, produktivitas, dan teknologi belum cukup tinggi untuk bersaing dengan negara maju.
Kelas menengah menyumbang hampir separuh konsumsi rumah tangga nasional. Namun demikian, survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) pada tahun 2024 menunjukkan hanya 17% penduduk Indonesia yang tergolong stabil di kelas ini, angka tersebut turun dari 23% pada 2018. Artinya, mayoritas kelas menengah kita sangat rentan jatuh kembali ke kelompok rentan miskin bila menghadapi guncangan kecil seperti kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan tinggi, atau inflasi pangan.
Kelas menengah di Indonesia sering kali hidup dengan gaya hidup “tampak naik kelas”, namun secara keuangan masih sangat terbatas. Banyak yang terjebak kredit konsumtif, tidak punya tabungan darurat, apalagi investasi. Akibatnya, ketika ekonomi terguncang, mereka kehilangan pondasi keuangan.
Jika dilihat dari sisi negara, jebakan ini muncul karena negara menengah seperti Indonesia tidak bisa lagi bersaing dengan negara upah murah (seperti Vietnam atau Bangladesh), tapi juga belum cukup kuat untuk bersaing dengan negara maju dalam hal inovasi dan teknologi. Akibatnya, pertumbuhan mandek, pendapatan stagnan, dan risiko stagnasi ekonomi jangka panjang pun membesar.
Beberapa kombinasi dari masalah struktural juga menjadi faktor pendukung “trap” ini seperti masih ketergantungan pada komoditas mentah, seperti ekspor batu bara, sawit, dan nikel mentah yang sangat bergantung pada harga global dan tidak menyerap tenaga kerja secara luas. Lalu masih rendahnya investasi manufaktur dan teknologi, tanpa transformasi ke sektor bernilai tambah tinggi, Indonesia terjebak di tengah: tak lagi murah, belum inovatif. Tak hanya itu, rendahnya kualitas SDM yang terjadi karena sistem pendidikan belum sepenuhnya membekali lulusan dengan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja masa depan. Dan yang terakhir yaitu masih berbelitnya birokrasi dan ketimpangan infrastruktur antardaerah.
Golongan Kelas Menengah
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu cara mengukur kelas ekonomi rumah tangga adalah melalui pengeluaran per kapita per bulan, yang kemudian dibagi dalam 10 kelompok bertingkat yang disebut desil. Desil 1 adalah kelompok 10% terbawah dengan pengeluaran paling rendah, sedangkan desil 10 adalah kelompok 10% teratas. Rumah tangga yang masuk dalam desil 4 sampai 7 biasanya dianggap sebagai bagian dari kelas menengah, dengan pengeluaran per kapita sekitar Rp800 ribu hingga Rp1,8 juta per bulan. Kalau kita asumsikan satu rumah tangga terdiri dari empat orang, maka pengeluaran rumah tangga kelas menengah berkisar di angka Rp3,2 juta hingga Rp7,4 juta per bulan. Namun angka itu tidak berdiri sendiri. LPEM FEB UI memberikan pendekatan yang lebih luas dan kontekstual. Mereka mengklasifikasikan kelas menengah Indonesia sebagai rumah tangga dengan pengeluaran antara Rp4 juta hingga Rp20 juta per bulan.
Indonesia pertama kali masuk kategori negara berpendapatan menengah pada tahun 2004, berdasarkan klasifikasi Bank Dunia. Saat itu, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Indonesia berhasil menembus ambang batas 1.136 dolar AS per tahun, yang menjadi syarat minimum negara menengah bawah. Sejak saat itu, status Indonesia terus bertahan di kelompok negara menengah. Pada tahun 2020, Indonesia sempat naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, tapi kemudian turun lagi akibat dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Baru pada tahun 2023, status negara menengah atas kembali diraih, dan masih bertahan sampai sekarang. Namun posisi Indonesia masih di level bawah dari kelompok ini, karena GNI per kapita kita baru sekitar 5.100 dolar AS per tahun, masih jauh dari ambang negara maju yang berada di atas 13.845 dolar AS.
Bank Dunia membagi negara berdasarkan GNI per kapita ke dalam empat kategori: berpendapatan rendah (di bawah 1.135 dolar AS), menengah bawah (1.136–4.465 dolar AS), menengah atas (4.466–13.845 dolar AS), dan berpendapatan tinggi (di atas 13.845 dolar AS). Meskipun begitu, posisi kita masih berada di ambang bawah kelompok menengah atas, artinya tantangan untuk naik ke kelompok negara maju jauh lebih besar dibandingkan saat naik dari negara miskin ke negara berkembang.
Perang Dagang dan Peluang
Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, dalam lima tahun terakhir, ekonomi Indonesia sempat terkontraksi saat pandemi tahun 2020. Tapi setelah itu, tumbuh stabil di kisaran 5% per tahun. Ini memang cukup untuk menjaga kestabilan ekonomi, tapi belum cukup tinggi untuk benar-benar membawa Indonesia keluar dari jebakan negara menengah. Banyak ahli menyebut, Indonesia perlu tumbuh minimal 6% atau lebih setiap tahun agar bisa naik kelas sebelum bonus demografi berakhir di 2040-an.
Apalagi, pada tahun ini tantangan semakin berat, perang dagang AS–Tiongkok yang kembali panas sejak 2024 mengguncang rantai pasok elektronik, (Electronic Vehicle) EV, dan semikonduktor. Tarif tit-for-tat menaikkan biaya impor komponen dan menekan ekspor bahan baku kita. Tarif tit-for-tat adalah strategi di mana suatu negara menerapkan tarif impor terhadap barang-barang dari negara lain sebagai balasan terhadap tarif yang diterapkan negara tersebut terhadap barang-barang yang diimpor dari negara tersebut. Ini adalah bentuk perang dagang yang melibatkan penerapan tarif atau hambatan perdagangan untuk membalas tindakan yang sama dari pihak lain. Kembali lagi ke perang dagang, efek fragmentasi rantai pasok ini juga membuka peluang besar bagi perusahaan multinasional dalam mencari “mitra netral” di kawasan Asia sebagai basis produksi. Indonesia, dengan pasar besar dan sumber daya melimpah, menjadi kandidat kuat.
Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini sebagai loncatan untuk keluar dari middle income trap. Salah satunya posisi sebagai pemasok nikel terbesar dunia memberi tawaran strategis bagi produsen baterai EV. Jika regulasi ramah investor, upaya green industrial park di Sulawesi dan Kalimantan, serta kemudahan logistik Pelabuhan Patimban terealisasi, Indonesia bisa menangkap arus investasi yang berpindah akibat perang dagang sehingga bisa mempercepat untuk keluar dari middle income trap.
Keluar dari Perangkap
Tak hanya dari momentum perang dagang ini saja, sejauh ini pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan berbagai peraturan serta kebijakan agar terhindar dari middle income trap. Salah satunya, pemerintah telah mengeksekusi strategi hilirisasi tambang lewat Permen ESDM 11/2019 yang melarang ekspor bijih nikel mentah. Kebijakan ini memaksa pembangunan belasan smelter, menarik Foreign Domestic Investment (FDI) miliaran dolar dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Eropa, serta menyiapkan ekosistem baterai EV dari Sulawesi hingga Maluku. Nilai ekspor produk nikel terolah melonjak hampir lima kali lipat dalam empat tahun terakhir, sembari menciptakan lapangan kerja industri.
Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 telah menyederhanakan 79 undang-undang menjadi satu kerangka besar untuk mempermudah investasi dan menyesuaikan pasar tenaga kerja. Ini menjadi pondasi bagus untuk melancarkan iklim investasi di Indonesia ke depannya. Tentu saja untuk keluar dari “perangkap” ini membutuhkan waktu yang tidak singkat serta estafet kebijakan yang konsisten antar pemerintahan.
Korea Selatan adalah contoh utama negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah. Butuh beberapa puluh tahun dan konsistensi kebijakan antar pemerintahan untuk mengubah Korea Selatan dari negara menengah menjadi negara maju. Pada tahun 1970-an, PDB per kapita Korsel setara dengan Indonesia. Namun, mereka memilih berinvestasi besar-besaran pada pendidikan, terutama sains dan teknologi. Pemerintah Korea Selatan juga membina kerja sama erat antara industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset, hingga akhirnya lahirlah Samsung, Hyundai, dan LG. Di benua biru, Irlandia adalah contoh lain. Pada 1990-an, Irlandia masih negara pendapatan menengah. Namun mereka menciptakan iklim investasi yang ramah pajak (<15%) dan mengembangkan sektor teknologi melalui FDI besar dari perusahaan seperti Apple, Google, dan Intel. Kini kedua negara tersebut menjadi negara maju dengan PDB per kapita di atas USD 30.000.
Tak lain dari skala makro, ekonomi rumah tangga juga bisa keluar dari jebakan ini. Meskipun tidak mudah, namun berikut beberapa langkah praktisnya. Dimulai dari investasi pada hal yang produktif. Sisihkan secara rutin minimal 20% penghasilan ke investasi seperti reksadana indeks, emas, saham blue chip, atau SBN. Setelah itu upgrade softskill yang dimiliki, seperti ikut pelatihan daring bersertifikat di bidang yang dibutuhkan pasar: data, teknologi, desain, bahasa, dll. Lalu bangun multiple income stream bisa dari freelance, bisnis online, dan aset produktif kecil yang dapat mengurangi risiko keuangan. Selain itu, disiplin akan utang, bedakan utang produktif (rumah, usaha) dengan konsumtif (gadget, gaya hidup). Dan yang terakhir, perluas jejaring karena banyak peluang karier dan usaha datang dari koneksi, bukan hanya prestasi.
Maju atau Terjebak Selamanya
Middle income trap bukan jargon akademik, tapi kenyataan yang kita rasakan saat ini mulai dari penghasilan stagnan, biaya hidup naik, dan mobilitas sosial yang mandek. Namun, ini bukan nasib. Pengalaman Korea Selatan dan Irlandia membuktikan bahwa dengan investasi jangka panjang di SDM, teknologi, dan reformasi struktural, jebakan ini bisa ditembus. Pemerintah Indonesia pun saat ini sedang melakukan hal yang sama. Di tengah berbagai tantangan global di 5 tahun terakhir, mulai dari Covid-19, Perang Rusia-Ukraina, hingga Perang Dagang di 2025 ini, pemerintah melalui APBN berhasil menjadi shock absorber sehingga tidak memperparah “trap”. Sementara itu, bagi skala rumah tangga kelas menengah bisa mulai dari hal-hal kecil seperti pengelolaan keuangan, keterampilan, dan relasi.
Pada akhirnya, pertarungan melawan middle income trap adalah maraton lintas-generasi. Apa yang kita bangun hari ini, dari memilih produk lokal bernilai tambah, menguasai keterampilan digital, sampai menuntut kebijakan ramah iklim, semua itu akan menentukan apakah anak-cucu kita masih berlari di treadmill yang sama, atau sudah menjejak jalur baru sebagai warga negara maju. Indonesia memiliki bonus demografi hingga awal 2040-an dan menargetkan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Kalau momentum ini hilang, jendela kesempatan itu akan tertutup. Maka, jadikan setiap keputusan yang kita lakukan saat ini sebagai investasi bersama untuk benar-benar bisa “naik kelas”, bukan sekadar bertahan di tengah. Karena dalam perang ekonomi jangka panjang ini, diam di tempat adalah bentuk kekalahan.
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Kategori: Kebijakan Fiskal