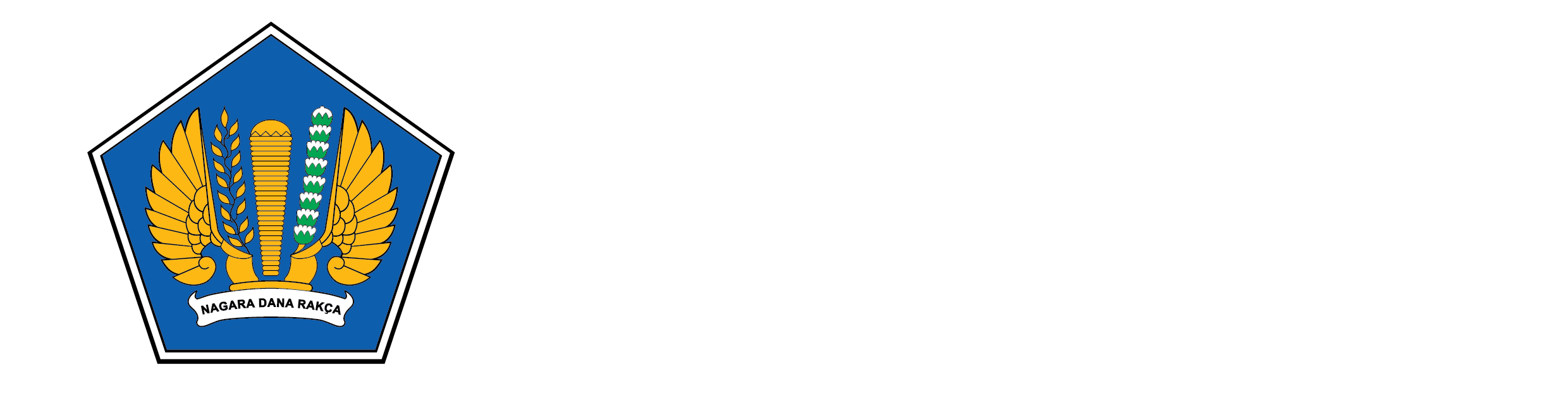Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah lama dikenal sebagai "surga timah." Sejarawan George Cœdès, seperti yang dikutip oleh Muhammad (2020), menyebutkan bahwa kemasyhuran Kep. Babel sebagai pulau timah terekam sejak ribuan tahun lalu dalam kitab sastra Millndrapantha dan kitab suci Hindu-Budha Nidessa, ketika pelaut India menyebut pulau ini sebagai "Wangka," yang berarti timah dalam bahasa Sansekerta. Dalam catatan perdagangan kuno, timah dari Babel telah menjadi komoditas utama yang diperdagangkan di jalur maritim Asia Tenggara. Kekayaan alam ini tidak hanya membentuk ekonomi Babel, tetapi juga identitas budayanya. Namun, seperti halnya segala sesuatu yang tak terbarukan, kejayaan timah perlahan memudar. Kini, pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak timah yang tersisa, melainkan apakah Babel mampu bertahan tanpa timah?
Dalam bayang-bayang kemilau timah yang kian memudar, muncul tantangan besar: ketergantungan ekonomi terhadap satu komoditas, degradasi lingkungan, hingga ancaman terhadap masa depan generasi muda. Sudah waktunya Babel menatap masa depan dengan langkah yang berani—melepas statusnya sebagai pulau timah dan membangun identitas baru yang lebih berkelanjutan.
Transformasi Ekonomi Babel
Sebagai komoditas tambang yang tidak dapat diperbarui, kejayaan timah di Kepulauan Bangka Belitung mulai meredup. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Babel, kontribusi sektor tambang timah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus mengalami penurunan selama 14 tahun terakhir. Pada tahun 2010, sub sektor industri logam dasar menyumbang 17,01% output ekonomi Babel, namun angkanya menurun drastis menjadi hanya 8,92% pada 2023. Sub sektor pertambangan bijih logam bahkan mencatat penurunan lebih tajam, dari 12,81% menjadi hanya 4,57% pada periode yang sama.
Sementara itu, beberapa sektor lain menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Sub sektor “Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda” kini menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 13,89% pada 2023. Sub sektor “Industri Makanan dan Minuman” juga tumbuh signifikan dari 5,51% pada 2010 menjadi 9,95% pada 2023. Sub sektor “Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian” serta perikanan turut memberikan kontribusi positif, meskipun masih menghadapi tantangan fluktuasi harga dan dampak lingkungan tambang timah.
Namun, transformasi ini belum cukup untuk melepaskan Babel dari jerat kutukan sumber daya alam (natural resource curse). Ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam seperti perkebunan dan perikanan tetap rentan terhadap fluktuasi pasar global dan degradasi lingkungan.
Dampak Sosial dan Lingkungan
Kerusakan lingkungan akibat tambang timah semakin nyata, baik di daratan maupun di lepas pantai. Lahan bekas tambang yang kehilangan unsur hara tidak lagi produktif untuk pertanian atau perkebunan. Sedangkan aktivitas tambang di laut merusak ekosistem terumbu karang, memaksa nelayan melaut lebih jauh untuk mencari ikan.
Dampak sosial juga tidak kalah mengkhawatirkan. Tambang ilegal yang marak menarik banyak pekerja, termasuk anak-anak, untuk mengejar keuntungan instan. Akibatnya, angka putus sekolah di Babel mencapai 3,5% pada 2020–2021, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 1,27%. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang semakin memperkuat ketergantungan Babel pada sektor tambang.
Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan
Untuk memutus siklus ketergantungan ini, Babel perlu mengambil langkah-langkah strategis. Dalam jangka pendek, pengawasan ketat terhadap tambang ilegal dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat membantu mengurangi dampak negatif tambang timah. Namun, tantangan utamanya adalah mendorong para penambang untuk memenuhi persyaratan legalitas dan kewajiban reklamasi.
Dalam jangka panjang, investasi pada pendidikan menjadi kunci utama. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu mengembangkan sektor-sektor baru, seperti industri jasa dan teknologi, yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, inovasi teknologi juga dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang sangat penting untuk menopang ketahanan pangan daerah.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di persimpangan sejarah. Ketergantungan terhadap timah telah membawa dampak ekonomi yang besar, namun juga menyisakan tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks. Diversifikasi ekonomi yang sudah mulai berjalan harus diperkuat dengan investasi jangka panjang pada pendidikan, teknologi, dan tata kelola lingkungan yang lebih baik.
Saatnya masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dengan mengutamakan pendidikan, pelestarian lingkungan, serta tata kelola sektor pertambangan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan peluang di sektor-sektor non-timah, Babel dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap komoditas ini dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Perubahan memang tidak mudah, tetapi langkah pertama harus diambil sekarang, sebelum semua yang kita miliki sirna bersama lenyapnya timah di Bumi Serumpun Sebalai.
Referensi
BPS Babel. (2024). [Tahunan] PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung. Babel.Bps.Go.Id. https://babel.bps.go.id/id/statistics-table/2/OCMy/-tahunan--pdrb-menurut-lapangan-usaha-atas-dasar-harga-berlaku.html
Muhammad, F. (2020). Cerita Kolong Timah Bangka di Masa Lalu Sampai Masa Sekarang. National Geographic. https://nationalgeographic.grid.id/read/132449726/cerita-kolong-timah-bangka-di-masa-lalu-sampai-masa-sekarang
Kategori: SDA
| 0 Komentar |
|---|