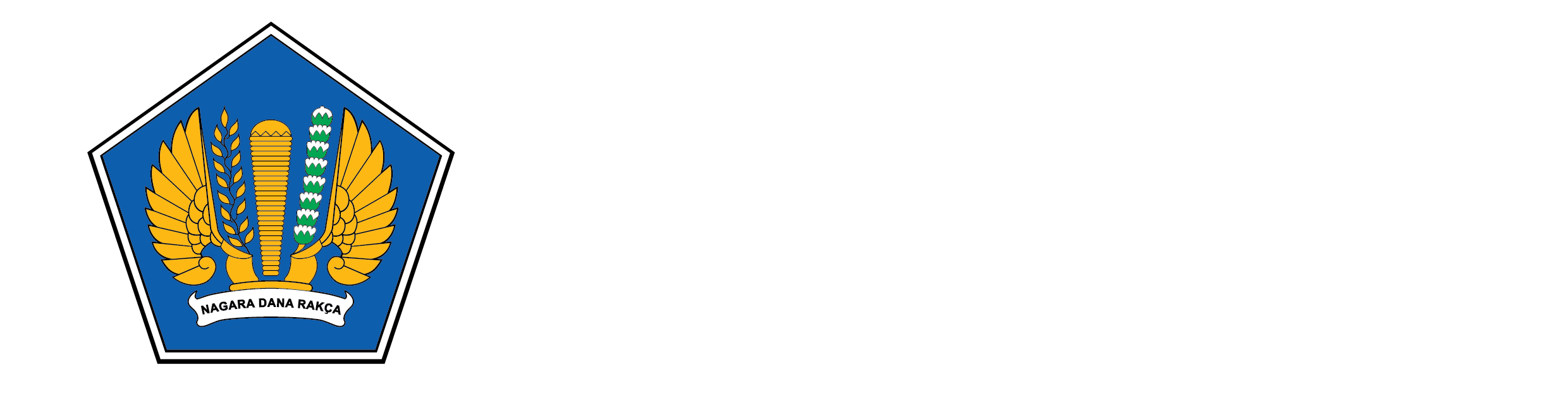Di tengah era yang serba cepat, dinamis, dan nyaris tanpa batas geografis, digitalisasi telah membawa gelombang perubahan besar pada seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dunia komunikasi publik. Humas pemerintah, sebagai ujung tombak komunikasi institusi negara, kini tidak hanya menghadapi tugas menyampaikan informasi, tetapi juga harus berjibaku dengan banjir data, disinformasi, dan perubahan drastis dalam cara publik mengonsumsi informasi. Tantangannya bukan hanya teknis, melainkan strategis dan struktural. Di sinilah pentingnya literasi informasi dan digital menjadi fondasi utama dalam merancang strategi komunikasi yang adaptif dan efektif.
Transformasi digital membawa kemudahan akses terhadap informasi, namun sekaligus membuka peluang besar bagi maraknya hoaks, clickbait, dan misinformasi. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ratusan konten hoaks tersebar setiap bulannya, mencakup isu sosial-politik hingga kebijakan publik. Dalam konteks inilah, humas pemerintah menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dari sekadar menyusun siaran pers atau mengelola akun media sosial.
Dulu, pemerintah adalah sumber informasi utama. Kini, ia bersaing dengan ribuan akun anonim, influencer, dan portal berita tak resmi yang bisa mempengaruhi opini publik dalam hitungan jam—bahkan menit. Dalam kondisi seperti ini, kredibilitas dan kecepatan menjadi mata uang baru dalam komunikasi.
Perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat mencari dan menyebarkan informasi. Konsumsi berita tak lagi didominasi media arus utama, melainkan bergeser ke media sosial, grup percakapan pribadi, dan konten video pendek. Riset dari We Are Social menunjukkan bahwa mayoritas pengguna internet Indonesia mengandalkan WhatsApp dan Instagram untuk mendapatkan informasi, bukan situs resmi pemerintah. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi humas pemerintah: bagaimana menyampaikan informasi strategis dalam format yang relevan, menarik, dan terpercaya bagi generasi digital? Di sinilah humas tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan konvensional. Diperlukan pendekatan omni-channel yang tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memahami perilaku digital masyarakat.
Literasi digital tidak hanya penting bagi masyarakat sebagai penerima informasi, tetapi juga bagi humas sebagai penyusun pesan. Literasi ini mencakup kemampuan memahami dinamika algoritma media sosial, membaca insight digital, memetakan jejaring informasi, hingga merespons crisis dengan pendekatan berbasis data.
Dalam kerangka teori Uses and Gratifications, publik bukan sekadar objek pasif yang menyerap informasi, melainkan subjek aktif yang memilih media dan konten berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya. Maka, humas harus mampu menyesuaikan format komunikasi dengan preferensi audiens: pendek, visual, interaktif, dan responsif. Lebih dari itu, humas harus bisa membedakan antara kecepatan dan akurasi. Di era banjir informasi, tergoda untuk segera menanggapi isu adalah hal yang umum, namun bisa menjadi bumerang bila dilakukan tanpa validasi. Oleh karena itu, literasi informasi juga mencakup kemampuan verifikasi cepat (real-time fact-checking) sebelum merilis klarifikasi.
Beberapa kasus komunikasi krisis menunjukkan kelemahan mendasar humas pemerintah. Misalnya, dalam penyampaian informasi terkait kebijakan darurat seperti pandemi atau bencana alam, sering kali terjadi keterlambatan atau ketidakkonsistenan narasi antar lembaga. Ini memperlihatkan kurangnya koordinasi dan pemahaman mendalam tentang karakteristik krisis digital yang mengharuskan kecepatan dan konsistensi. Sebaliknya, keberhasilan kampanye publik seperti vaksinasi COVID-19 di beberapa daerah menunjukkan kekuatan sinergi antara humas pemerintah, tokoh masyarakat, dan kanal digital lokal. Pendekatan ini tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik lewat keterlibatan emosional dan sosial.
Teori Agenda-Setting oleh McCombs dan Shaw menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Pemerintah harus mampu menetapkan agenda isu yang dianggap penting oleh publik. Namun di era digital, agenda-setting tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh institusi resmi. Kekuasaan itu kini tersebar—terdesentralisasi—ke tangan pengguna media sosial. Oleh sebab itu, humas harus cermat memilih isu, narasi, dan waktu penyampaian agar bisa menjadi bagian dari diskursus digital, bukan hanya berteriak di ruang hampa.
Selain itu, pendekatan dialogic communication dari Kent dan Taylor menekankan pentingnya komunikasi dua arah dalam membangun hubungan yang bermakna antara institusi dan publik. Dalam kerangka ini, strategi komunikasi tidak hanya soal menyampaikan, tetapi juga soal mendengarkan, menanggapi, dan menyesuaikan kebijakan dengan aspirasi yang muncul dari bawah.
Berikut beberapa langkah strategis yang bisa diambil humas pemerintah untuk menghadapi tantangan disrupsi digital dan literasi informasi:
- Peningkatan Kapasitas Digital
Pelatihan reguler bagi tim humas mengenai media monitoring, fact-checking tools, dan content analytics menjadi kebutuhan mendesak. - Kolaborasi dengan Komunitas Digital
Melibatkan influencer, jurnalis warga, dan komunitas digital lokal dapat membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih organik dan dipercaya. - Penguatan Protokol Respons Krisis Digital
Humas perlu memiliki standar operasional untuk merespons isu viral secara cepat, akurat, dan terkoordinasi lintas sektor. - Diversifikasi Format dan Kanal Komunikasi
Tidak semua informasi harus disampaikan dalam format teks panjang atau konferensi pers. Infografis, podcast, video pendek, hingga meme—bila dikelola profesional—bisa menjadi kanal efektif menyasar segmen muda. - Membangun Kultur Keterbukaan
Komitmen terhadap keterbukaan informasi dan transparansi harus menjadi fondasi, bukan sekadar slogan. Hal ini termasuk membuka ruang dialog secara digital melalui kanal resmi dan terverifikasi.
Disrupsi digital adalah keniscayaan. Ia bukan hanya soal teknologi, tetapi perubahan cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Humas pemerintah tidak bisa lagi bersembunyi di balik rilis pers formal atau menutup komentar publik di media sosial. Ke depan, keberhasilan komunikasi publik akan ditentukan oleh seberapa lincah, cerdas, dan terbuka humas dalam menghadapi tantangan digital yang terus berubah.
Literasi informasi bukan lagi pelengkap, tetapi fondasi. Karena di era di mana informasi bisa dibuat oleh siapa saja dan disebarkan dalam hitungan detik, humas pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai sumber resmi, tetapi juga sebagai penjaga akal sehat publik.
Kategori: Sinergi
| 0 Komentar |
|---|